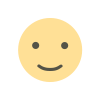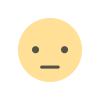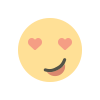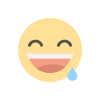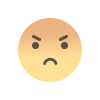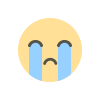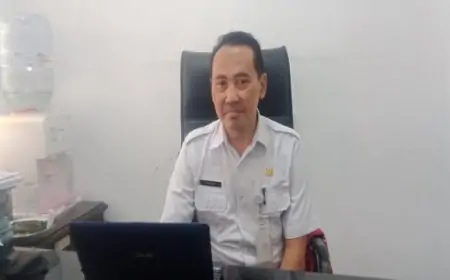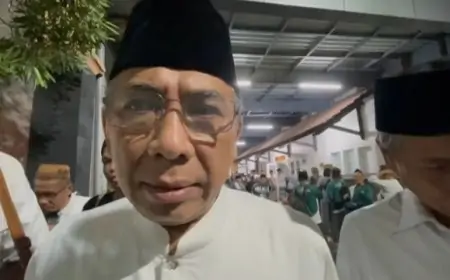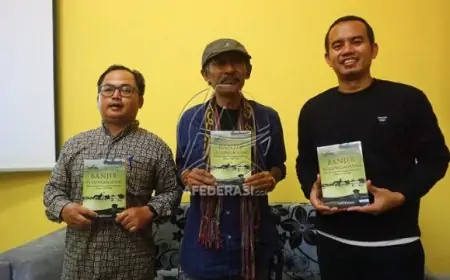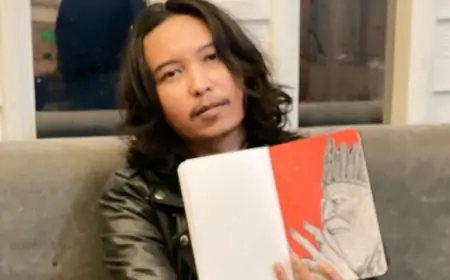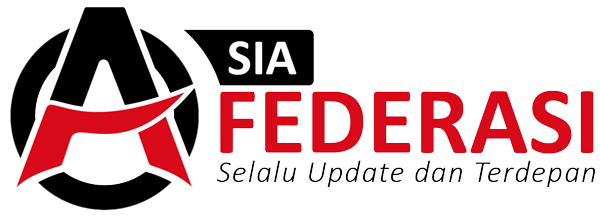Merdeka dari Kelaparan: Program Makan Bergizi Gratis dan Cermin Ketimpangan Sosial

Jombang, (afederasi.com) – Tahun 2025 menjadi tonggak sejarah penting bagi Indonesia. Tepat 80 tahun sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, bangsa ini masih menghadapi tantangan mendasar: kelaparan dan ketimpangan sosial yang membayangi masa depan anak-anaknya.
Di tengah semarak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia ke-80, pemerintah meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari visi “Indonesia Emas 2045”.
Program ini menyasar pelajar, terutama dari keluarga kurang mampu, sebagai bentuk intervensi negara untuk menekan angka stunting dan gizi buruk.
Namun, di balik semangat positif yang dibangun, muncul pertanyaan mendasar: Apakah program ini benar-benar solusi, atau sekadar simbol politik dalam balutan populisme?
Endah Wahyuningsih, S.Sos., M.Sosio., Dosen dan Peneliti Sosiologi FISIP Universitas Darul Ulum (Undar) Jombang, menilai bahwa MBG bukan sekadar kebijakan gizi, tapi mencerminkan dinamika sosial-politik yang lebih dalam.
“Program ini tampak sebagai langkah solutif terhadap stunting, tapi secara sosiologis, ia menyimpan makna politis, simbolik, dan struktural yang mencerminkan kondisi sosial bangsa kita,” ungkapnya kepada afederasi.com.
Dari perspektif fungsionalisme struktural, negara hadir memenuhi tanggung jawabnya—sekolah kini tidak hanya tempat belajar, tapi juga pusat distribusi nutrisi.
Namun, pendekatan ini menyiratkan kegagalan negara dalam menjamin hak dasar rakyat, termasuk kedaulatan pangan seperti diamanatkan UUD 1945 Pasal 28H dan Pasal 34.
Sementara itu, teori konflik memandang MBG sebagai respons negara untuk meredam gejolak akibat ketimpangan sosial yang menganga. Negara memberi makan, tapi belum mampu menyejahterakan.
Di usia 80 tahun kemerdekaan, masih ada jutaan anak yang bergantung pada makan gratis—sebuah ironi yang menohok sistem ekonomi nasional.
Program ini diluncurkan dalam momentum politik yang strategis. Negara tampil seolah pelindung rakyat kecil, terutama anak-anak. Ini sejalan dengan konsep politics of recognition atau politik pengakuan—di mana negara mencari legitimasi melalui kebijakan populis.
Narasi resmi menggambarkan MBG sebagai bentuk gotong royong modern, simbol keadilan sosial, dan investasi masa depan. Namun, tanpa reformasi struktural yang nyata, program ini dikhawatirkan hanya akan menjadi gimik politik sesaat, bukan solusi jangka panjang.
Lebih jauh lagi, dari perspektif interaksionisme simbolik, MBG berisiko menimbulkan stigma sosial. Jika program ini dilabeli hanya untuk “anak miskin”, maka bisa menciptakan rasa malu, minder, bahkan eksklusi sosial di kalangan pelajar.
Tak hanya itu, muncul pula risiko sindrom ketergantungan (dependency syndrome). Ketika masyarakat hanya menerima tanpa diberdayakan, nilai-nilai kemandirian yang menjadi semangat kemerdekaan justru tergerus.
Dalam pendekatan konstruktivisme sosial, “gizi” bukanlah konsep netral. Negara dan lembaga teknokratis menentukan standar, menu, bahkan cara makan. Di sinilah muncul pertanyaan: Apakah program ini menghargai kearifan lokal dan budaya pangan daerah?
Tanpa sensitivitas budaya, MBG bisa berujung pada homogenisasi pangan, mengabaikan sumber gizi lokal yang lebih relevan dan ramah lingkungan.
Bahkan, melalui perspektif biopolitik ala Michel Foucault, negara dianggap sedang mengontrol tubuh rakyatnya—mengatur apa yang boleh dikonsumsi, bagaimana tubuh tumbuh, dan seperti apa standar "gizi baik" itu dibentuk.
Delapan dekade merdeka, Indonesia seharusnya sudah mencapai kemandirian pangan dan keadilan sosial. Namun, fakta bahwa jutaan anak masih bergantung pada makan gratis adalah refleksi bahwa kemiskinan masih multidimensi, dan pembangunan belum merata, terutama antara Jawa dan luar Jawa, serta antara kota dan desa.
Jika MBG hanya menjadi proyek citra dan statistik, maka kemerdekaan kita belum menyentuh makna substantif.
Tapi jika dijadikan pintu masuk reformasi sistem pangan, pemberdayaan ekonomi keluarga, dan distribusi sumber daya yang adil, maka program ini bisa menjadi warisan monumental menuju Indonesia Emas.
Kini saatnya bertanya dengan jujur: Apakah kita benar-benar merdeka jika masih banyak anak yang bertahan hidup dari makan gratis?
Kemerdekaan sejati bukan hanya soal bebas dari penjajah, tapi juga bebas dari kelaparan, ketergantungan, stigma, dan ketimpangan struktural.
MBG bukan tujuan akhir, melainkan titik awal menuju sistem sosial yang adil, inklusif, dan berdaulat pangan.Karena pada akhirnya, Indonesia akan benar-benar merdeka saat setiap anak bisa makan bergizi tanpa harus diberi. (san)
What's Your Reaction?