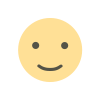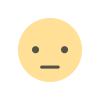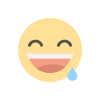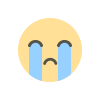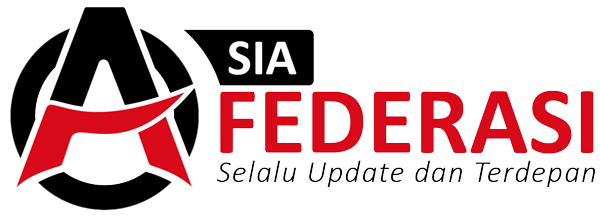Jangan Ada “Bencana” di Lereng Ijen

Bondowoso, (afederasi.com) - Ketika tiga provinsi di Pulau Sumatera luluh lantak oleh bencana alam, kita berdebat tentang akar masalahnya. Ketika Sampit “banjir darah”, kita juga beradu argumentasi. Ketika, ketika, ketika...dan terus terjadi, berulang.
Hari ini, kita tampak baik-baik saja. Insiden-insiden sporadis dianggap sesuatu yang lumrah sebagaimana dunia yang niscaya ada baik ada jahat. Preseden-preseden buruk sering tak diselesaikan secara tuntas, dibiarkan, bahkan ada yang menganggap hanya sebagai gimmick, cuma ramai di media sosial.
Salah satu insiden aktual adalah konflik di Lereng Ijen, Bondowoso, Jawa Timur. Yakni, perusakan ribuan tanaman kopi milik PTPN I Regional 5 yang kembali berulang. Bahkan, pada peristiwa November 2025 lalu, ada drama tragis yang boleh disebut “pelecehan“ terhadap simbol negara; seorang Kapolsek “dipelonco“ oleh warga beramai-ramai dengan kesadaran bersama.
Aksi perusakan lebih dari 17.000 pohon kopi di Afdeling Kalisengon, Kebun JCE–Blawan, bukan lagi sekadar angka dalam laporan kerugian aset negara. Secara sosiologis, pembabatan massal ini merupakan provokasi ekstrem yang sangat berbahaya. Jika tidak segera dipadamkan dengan pendekatan yang tepat, insiden ini akan memicu konflik sosial ibarat api dalam sekam. Ini adalah ancaman bencana sosial yang lebih sulit dipulihkan dibanding memulihkan bencana Sumatera.
Jika terjadi, ini akan memperhadapkan masyarakat dengan tetangganya sendiri dalam sebuah konflik horizontal yang destruktif di jantung dataran tinggi Ijen. Dan ketika nasi sudah menjadi bubur, kita akan berdebat lagi mengapa ini terjadi? Mengapa pemerintah tidak mengantisipasi? Mengapa negara tidak hadir sebelum semua menjadi arang? Mengapa para tokoh tidak ini, tidak itu? Mengapa dan terus mengapa? Sayangnya, pertanyaan beruntun itu hanya menghasilkan bahan baku skripsi, thesis, atau disertasi para akademisi. Sementara, luka akan tetap membekas dan menjadi sejarah kelam bangsa ini.
Dalam kasus perusakan kebun kopi di Kawasan Ijen, selama ini diskursus publik sering kali terjebak pada pandangan dikotomis yang menyederhanakan persoalan sebagai perselisihan vertikal antara masyarakat melawan korporasi. Namun, realitas empiris di lapangan menunjukkan pergeseran peta konflik yang jauh lebih mengkhawatirkan.
Dengan keterlibatan sekitar 3.500 karyawan yang mayoritas merupakan warga asli Bondowoso, setiap batang pohon kopi yang ditebang secara brutal sejatinya adalah serangan langsung terhadap urat nadi ekonomi sesama warga.
Data menunjukkan bahwa untuk memulihkan 17.499 pohon yang rusak, diperlukan waktu setidaknya 3 hingga 5 tahun hingga tanaman kembali produktif. Itupun dengan investasi yang sangat besar. Artinya, ancaman ini adalah pemiskinan jangka panjang bagi ribuan keluarga. Perusakan ini, pada hakikatnya, merupakan teror ekonomi terhadap rakyat kecil yang kerap dibungkus dengan eufemisme sengketa lahan.
Dampaknya bersifat sistemik; bagi karyawan, hilangnya tanaman berarti pupusnya harapan akan kesejahteraan. Di sisi lain, ekosistem ekonomi Kecamatan Ijen—mulai dari sektor transportasi hingga UMKM—turut lumpuh akibat terhentinya perputaran uang dari sektor perkebunan.
Di balik aksi anarkis ini, para pemantik konflik—mulai dari oknum politikus, pemodal, penjamin, hingga tokoh lembaga—harus menyadari bahwa setiap konsep, perintah, dan tindakan yang mereka lakukan berdampak pada bom waktu bernama "konflik sosial". Patut dipertanyakan: apakah konflik yang timbul ini benar-benar akan menyejahterakan masyarakat? Ataukah masyarakat hanya dijadikan "benteng hidup" untuk kepentingan segelintir elite?
Lebih jauh lagi, muncul fenomena memprihatinkan terkait doktrin kepada masyarakat tentang narasi "berjihad" untuk mempertahankan lahan yang secara hukum bukan miliknya. Kita harus merenungkan kembali, apakah pembenaran atas nama agama untuk tindakan destruktif dan perebutan hak yang tidak sah dapat dibenarkan secara moral dan teologis..? Apakah ada jaminan jika lahan tersebut nantinya dikuasai secara sepihak, masyarakat kecil benar-benar akan mendapatkan bagian secara adil? Ataukah mereka kembali hanya menjadi pion dalam perebutan ruang kekuasaan?
Saat ribuan karyawan merasa "periuk nasi" mereka dihancurkan, sentimen kebencian akan tumbuh subur, menciptakan suasana saling curiga di pasar, desa, hingga tempat ibadah. Potensi benturan fisik antara pekerja yang menjaga ladang penghidupannya dengan kelompok perusak kini berada pada titik didih tertinggi.
Skala kerusakan yang masif dan terorganisir ini mengirimkan pesan intimidasi bahwa hukum seolah tidak berdaya. Jika negara tidak segera hadir memberikan kepastian hukum, terdapat risiko besar munculnya tindakan main hakim sendiri (vigilantisme) dari pihak yang merasa terhimpit ekonominya.
Penyelesaian kemelut di Kebun Blawan kini menuntut pendekatan yang melampaui penjagaan fisik. Diperlukan kehadiran negara secara utuh melalui mediasi agraria yang transparan serta ketegasan hukum terhadap para aktor intelektual di balik layar.
Negara harus memastikan bahwa hak atas pekerjaan 3.500 warga tidak kalah oleh aksi anarkis kelompok tertentu yang berlindung di balik isu agraria. Kita tidak boleh menunggu jatuhnya korban jiwa atau hancurnya tatanan sosial secara permanen untuk menyadari bahwa harmoni di lereng Ijen sedang berada di tepi jurang kehancuran. (*)
Andi Firmasyah, Pengamat sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan. Alumnus Universitas Muhammadiyah Lampung.
What's Your Reaction?